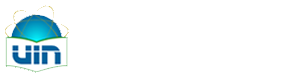Menteri Agama Kukuhkan Pengurus ASKOPIS di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Dalam rangkaian pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, muncul dua isu yang berkaitan dengan masjid. Pertama, gagasan Menteri Agama untuk membuat aturan tentang ceramah dan khutbah di masjid. Kedua, maraknya spanduk di masjid—khususnya sejumlah masjid di Jakarta—yang menyatakan sebagai “pembela ulama”, “pendukung FPI (Front Pembela Islam)—ormas Islam yang dikenal berhaluan keras—dan, yang paling akhir, “penolakan untuk menshalatkan jenazah pemilih pemimpin kafir”. Kedua isu itu menunjukkan bahwa masjid telah menjadi arena kompetisi dalam rangkaian peristiwa politik kontemporer.
Masjid merupakan bangunan penting dalam Islam. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah (arti bahasa: “tempat bersujud”), tetapi juga tampil dengan fungsi-fungsi lain yang bersifat sosial dan pendidikan. Dan barangkali perlu ditambahkan dimensi politik. Pada periode awal Islam, masjid telah melayani masyarakat Muslim sebagai tempat “berinteraksi sosial dan belajar” (thalab al-ilm) sekaligus. Di dalam masjid biasanya berlangsung halaqah (“lingkaran”) yang terdiri dari guru-murid untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman atau mendiskusikan masalah agama. Pada masa Nabi saw., yang bertindak sebagai guru adalah Nabi saw., sendiri dan para sahabat sebagai para muridnya.
Bahkan pada masa-masa itu pernah dikenal istilah masjid-khan (“asrama di samping masjid”), sebagai tempat menginap para pelajar dari tempat yang jauh. Istilah itu muncul karena dominasi masjid sebagai tempat belajar. Dalam sejarah, fungsi masjid sebagai tempat belajar ini pernah menjadi sangat penting—khususnya sebelum kemunculan tempat-tempat belajar dalam bentuk kelembagaan seperti madrasah diniyah (di masa lalu) atau taman belajar al-Qur’an (di masa kontemporer sekarang ini).
Fungsi masjid tersebut tidak semakin surut sepanjang zaman. Muslim tampaknya bahkan semakin menyadari bahwa masjid juga merupakan lembaga keislaman. Oleh karena itu, belakangan ini aktivitas yang berlangsung di masjid—apakah itu di Indonesia atau negara-negara Muslim lain—justru semakin meningkat. Masjid muncul tidak hanya dalam bentuk arsitektur yang khas, tetapi juga dengan manajemen pengelolaan masjid yang modern. Bahkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, terdapat Program Studi Manajemen Dakwah, yang menjadikan manajemen masjid modern menjadi mata kuliah inti di dalamnya.
Indonesia—dengan mayoritas penduduk adalah Muslim—memiliki banyak sekali masjid. Menurut data Kementerian Agama 2013, paling tidak terdapat lebih dari 292.439 ribu masjid yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah sebesar itu yang berkombinasi dengan kesungguhan para pengelolanya dalam mewujudkan cita-cita pengelolaan masjid secara modern telah melahirkan gerakan sosial-keagamaan—yang muncul dari masjid. Salah satunya diwujudkan dengan membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada dekade 1970-an—sekarang dipimpin Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden RI. DMI kemudian muncul dengan program-program pelatihan manajemen pengelolaan masjid.
DMI sendiri sebenarnya merupakan fusi dari beberapa organisasi kemasjidan yang sudah semarak pada periode sebelum 1970-an. Mereka yang berfusi adalah: Persatuan Masjid Indonesia (PERMI); Ikatan Masjid dan Mushalla Indonesia (IMAMI); Ikatan Masjid Indonesia (IKMI); Majelis Ta’miril Masjid Muhammadiyah; Hai’ah Ta’miril Masjid Indonesia (HTMI); Ikatan Masjid dan Mushalla Indonesia Muttahidah (IMMIM); Majelis Kemasjidan Al-Washliyah; Majelis Kemasjidan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Fakta banyaknya organisasi kemasjidan ini menunjukkan bahwa masjid telah memainkan fungsi sebagai tempat ibadah, sosial, dan bahkan politik, sudah sejak lama di Indonesia.
Banyaknya organisasi kemasjidan itu sebagian merupakan cermin dari kesadaran Muslim bahwa masjid merupakan lembaga strategis dalam konteks disemminasi ideologi-keagamaan. Masjid merupakan meeting point di antara sesama Muslim yang di dalamnya tidak hanya terjadi interaksi individual, tetapi juga kelompok dengan ideologi dan tafsir keagamaan. Posisi masjid seperti inilah yang menjelaskan mengapa masjid kemudian seperti muncul sebagai “arena kompetisi” antara ideologi keagamaan. Sebuah cerita di Jurnal Muhammadiyah, “Sendang Ayu: Pergulatan Muhammadiyah di kaki Bukit Barisan” (2006), menarik dikutip di sini. Peristiwanya berkenaan dengan “masuknya” kelompok yang berafiliasi kepada partai politik Islam tertentu ke dalam sebuah masjid kecil di desa Sendang Ayu. Masjid kecil yang dikelola warga Muhammadiyah ini, yang tadinya adem dan netral, tiba-tiba kental dengan dimensi politik dan berubah menjadi menghujat kelompok lain, bahkan mengkafirkan.
Peristiwa Sendang Ayu tersebut merupakan catatan penting. Karena peristiwa itu menandai munculnya kesadaran bahwa masjid seperti sedang diperebutkan di antara kelompok-kelompok Islam. Mereka berkompetisi dalam menyebarluaskan (atau mendakwahkan) ideologi-keagamaan tertentu di Indonesia. Tampilnya spanduk-spanduk dukungan politik di masjid, seperti disebutkan, tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi printing, tetapi indikator menguatnya aspirasi Islam bercorak radikal di Indonesia. Melihat perkembangan ini, gagasan Menteri Agama—meskipun juga merupakan bagian dari kompetisi merebut masjid—harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh.
Dalam rangkaian pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, muncul dua isu yang berkaitan dengan masjid. Pertama, gagasan Menteri Agama untuk membuat aturan tentang ceramah dan khutbah di masjid. Kedua, maraknya spanduk di masjid—khususnya sejumlah masjid di Jakarta—yang menyatakan sebagai “pembela ulama”, “pendukung FPI (Front Pembela Islam)—ormas Islam yang dikenal berhaluan keras—dan, yang paling akhir, “penolakan untuk menshalatkan jenazah pemilih pemimpin kafir”. Kedua isu itu menunjukkan bahwa masjid telah menjadi arena kompetisi dalam rangkaian peristiwa politik kontemporer.
Masjid merupakan bangunan penting dalam Islam. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah (arti bahasa: “tempat bersujud”), tetapi juga tampil dengan fungsi-fungsi lain yang bersifat sosial dan pendidikan. Dan barangkali perlu ditambahkan dimensi politik. Pada periode awal Islam, masjid telah melayani masyarakat Muslim sebagai tempat “berinteraksi sosial dan belajar” (thalab al-ilm) sekaligus. Di dalam masjid biasanya berlangsung halaqah (“lingkaran”) yang terdiri dari guru-murid untuk mengajarkan ilmu-ilmu keislaman atau mendiskusikan masalah agama. Pada masa Nabi saw., yang bertindak sebagai guru adalah Nabi saw., sendiri dan para sahabat sebagai para muridnya.
Bahkan pada masa-masa itu pernah dikenal istilah masjid-khan (“asrama di samping masjid”), sebagai tempat menginap para pelajar dari tempat yang jauh. Istilah itu muncul karena dominasi masjid sebagai tempat belajar. Dalam sejarah, fungsi masjid sebagai tempat belajar ini pernah menjadi sangat penting—khususnya sebelum kemunculan tempat-tempat belajar dalam bentuk kelembagaan seperti madrasah diniyah (di masa lalu) atau taman belajar al-Qur’an (di masa kontemporer sekarang ini).
Fungsi masjid tersebut tidak semakin surut sepanjang zaman. Muslim tampaknya bahkan semakin menyadari bahwa masjid juga merupakan lembaga keislaman. Oleh karena itu, belakangan ini aktivitas yang berlangsung di masjid—apakah itu di Indonesia atau negara-negara Muslim lain—justru semakin meningkat. Masjid muncul tidak hanya dalam bentuk arsitektur yang khas, tetapi juga dengan manajemen pengelolaan masjid yang modern. Bahkan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, terdapat Program Studi Manajemen Dakwah, yang menjadikan manajemen masjid modern menjadi mata kuliah inti di dalamnya.
Indonesia—dengan mayoritas penduduk adalah Muslim—memiliki banyak sekali masjid. Menurut data Kementerian Agama 2013, paling tidak terdapat lebih dari 292.439 ribu masjid yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah sebesar itu yang berkombinasi dengan kesungguhan para pengelolanya dalam mewujudkan cita-cita pengelolaan masjid secara modern telah melahirkan gerakan sosial-keagamaan—yang muncul dari masjid. Salah satunya diwujudkan dengan membentuk sebuah organisasi yang disebut dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada dekade 1970-an—sekarang dipimpin Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden RI. DMI kemudian muncul dengan program-program pelatihan manajemen pengelolaan masjid.
DMI sendiri sebenarnya merupakan fusi dari beberapa organisasi kemasjidan yang sudah semarak pada periode sebelum 1970-an. Mereka yang berfusi adalah: Persatuan Masjid Indonesia (PERMI); Ikatan Masjid dan Mushalla Indonesia (IMAMI); Ikatan Masjid Indonesia (IKMI); Majelis Ta’miril Masjid Muhammadiyah; Hai’ah Ta’miril Masjid Indonesia (HTMI); Ikatan Masjid dan Mushalla Indonesia Muttahidah (IMMIM); Majelis Kemasjidan Al-Washliyah; Majelis Kemasjidan Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Fakta banyaknya organisasi kemasjidan ini menunjukkan bahwa masjid telah memainkan fungsi sebagai tempat ibadah, sosial, dan bahkan politik, sudah sejak lama di Indonesia.
Banyaknya organisasi kemasjidan itu sebagian merupakan cermin dari kesadaran Muslim bahwa masjid merupakan lembaga strategis dalam konteks disemminasi ideologi-keagamaan. Masjid merupakan meeting point di antara sesama Muslim yang di dalamnya tidak hanya terjadi interaksi individual, tetapi juga kelompok dengan ideologi dan tafsir keagamaan. Posisi masjid seperti inilah yang menjelaskan mengapa masjid kemudian seperti muncul sebagai “arena kompetisi” antara ideologi keagamaan. Sebuah cerita di Jurnal Muhammadiyah, “Sendang Ayu: Pergulatan Muhammadiyah di kaki Bukit Barisan” (2006), menarik dikutip di sini. Peristiwanya berkenaan dengan “masuknya” kelompok yang berafiliasi kepada partai politik Islam tertentu ke dalam sebuah masjid kecil di desa Sendang Ayu. Masjid kecil yang dikelola warga Muhammadiyah ini, yang tadinya adem dan netral, tiba-tiba kental dengan dimensi politik dan berubah menjadi menghujat kelompok lain, bahkan mengkafirkan.
Peristiwa Sendang Ayu tersebut merupakan catatan penting. Karena peristiwa itu menandai munculnya kesadaran bahwa masjid seperti sedang diperebutkan di antara kelompok-kelompok Islam. Mereka berkompetisi dalam menyebarluaskan (atau mendakwahkan) ideologi-keagamaan tertentu di Indonesia. Tampilnya spanduk-spanduk dukungan politik di masjid, seperti disebutkan, tidak hanya berkaitan dengan kemajuan teknologi printing, tetapi indikator menguatnya aspirasi Islam bercorak radikal di Indonesia. Melihat perkembangan ini, gagasan Menteri Agama—meskipun juga merupakan bagian dari kompetisi merebut masjid—harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh.